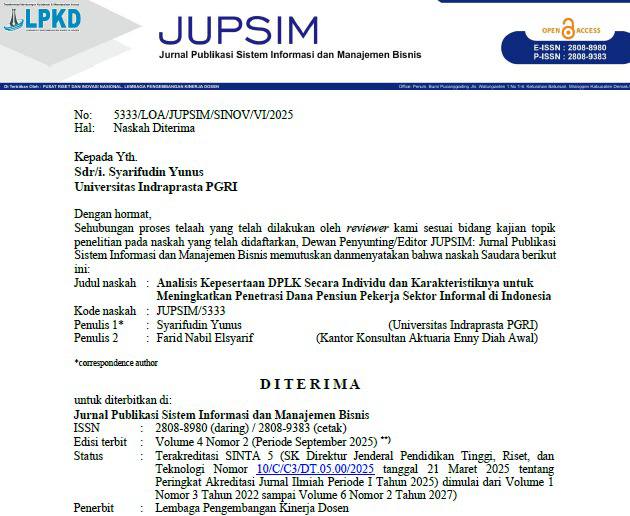Pensiunan PT Chevron Pacific Indonesia. Menjadi Pemerhati aspal Buton sejak 2005.
Paradoks Impor Aspal: Menjual Harga Diri demi Membeli Jalan Sendiri
3 jam lalu
Paradoks impor aspal adalah potret diri bangsa Indonesia yang rapuh, karena kehilangan visi jangka panjang.
***
Indonesia adalah negara dengan cadangan aspal alam terbesar di dunia, tetapi tetap menjadi pembeli setia aspal impor. Ironisnya, kita membayar mahal untuk bahan yang sebenarnya sudah tersedia di halaman rumah kita sendiri. Setiap tahun, miliaran rupiah devisa mengalir keluar negeri demi aspal minyak. Seakan harga diri bangsa ini tidak lebih berharga daripada selembar kontrak impor aspal.
Aspal Buton adalah anugerah yang tidak dimiliki negara lain. Pulau kecil di Sulawesi Tenggara itu menyimpan lebih dari 650 juta ton cadangan aspal alam. Jumlah ini cukup untuk membangun jalan dari Sabang sampai Merauke selama ratusan tahun. Tetapi anugerah itu justru kita biarkan terkubur, sementara kapal-kapal pengangkut aspal impor terus berdatangan.
Kita sering bangga menyebut diri sebagai bangsa besar yang berdikari. Namun dalam urusan aspal, kita justru jongkok di hadapan para negara pemasok. Setiap kali harga minyak dunia naik, biaya pembangunan jalan di Indonesia ikut melonjak. Dan di saat yang sama, Buton hanya bisa diam melihat kekayaannya terus terabaikan.
Inilah paradoks paling telanjang dalam sejarah infrastruktur kita. Kita punya bahan baku melimpah, tetapi memilih membeli aspal dari luar negeri. Kita bicara soal efisiensi anggaran, tetapi membuang triliunan rupiah devisa setiap tahun. Semua itu demi mempertahankan mata rantai bisnis impor aspal yang hanya menguntungkan segelintir pihak.
Membeli aspal impor bukan sekadar pemborosan uang, tetapi juga pengkhianatan terhadap potensi bangsa. Kita menggadaikan kesempatan kerja, teknologi, dan kemajuan industri nasional demi kenyamanan instan. Ironisnya, rakyat yang hidup di atas tambang aspal malah membayar jalan dengan harga yang lebih mahal. Inilah bentuk jual mahal yang justru merugikan diri sendiri.
Bayangkan jika kita memproses sendiri aspal Buton. Setiap proyek jalan akan membayar tenaga kerja lokal, bukan rekening perusahaan asing. Setiap rupiah akan berputar di ekonomi daerah, bukan menguap keluar negeri. Itulah esensi kedaulatan yang kita abaikan selama puluhan tahun.
Para pembuat kebijakan sering berdalih soal kualitas dan teknologi. Padahal teknologi ekstraksi pengolahan aspal Buton sudah siap. Banyak pabrik bisa dibangun jika ada kemauan politik. Tetapi kemauan itu kalah oleh kekuatan jaringan impor aspal yang sudah mengakar.
Kita membanggakan UUD 1945 Pasal 33, tetapi membiarkannya jadi hiasan dinding. “Bumi, air, dan kekayaan alam dikuasai negara untuk kemakmuran rakyat” hanya indah di buku pendidikan. Dalam praktiknya, kekayaan itu justru dikuasai pasar global. Rakyat hanya jadi penonton yang membayar tiket masuk lewat pajak.
Lebih menyakitkan lagi, banyak jalan di Buton sendiri diaspal dengan bahan impor. Ini seperti nelayan yang makan ikan kalengan dari luar negeri, sementara lautnya penuh ikan segar. Rasanya bukan hanya ironi, tetapi juga penghinaan terhadap akal sehat. Bagaimana mungkin ini bisa dibenarkan?
Paradoks ini membuat kita membayar dua kali. Pertama, kita kehilangan potensi pendapatan dari pengolahan aspal sendiri. Kedua, kita membayar lebih mahal untuk membeli barang yang sebenarnya tersedia gratis dari bumi kita sendiri. Semua karena kita memilih jalan pintas yang sebenarnya memutar lebih jauh.
Jika kita terus bergantung pada impor aspal, kita sedang menulis kontrak kemiskinan jangka panjang. Harga aspal impor bisa naik kapan saja sesuai permainan pasar. Saat itu terjadi, proyek-proyek akan terhenti, dan rakyatlah yang menanggung akibatnya. Sementara mafia impor aspal tetap tersenyum lebar di balik layar.
Banyak negara kecil mampu memaksimalkan sumber daya alamnya untuk membebaskan diri dari ketergantungan. Tetapi kita, dengan semua potensi yang ada, malah sibuk mencari alasan. Kita takut pada resiko, tetapi tidak takut kehilangan kedaulatan. Seolah harga diri bangsa bisa ditukar murah dengan beberapa juta ton aspal impor.
Yang lebih parah lagi, ketergantungan ini membunuh inovasi lokal. Industri aspal dalam negeri tidak pernah tumbuh karena selalu kalah bersaing dengan barang impor. Anak-anak muda yang punya teknologi baru untuk aspal Buton tidak mendapat ruang berkembang. Padahal, dari sinilah seharusnya lahir kemandirian.
Paradoks impor aspal adalah potret diri bangsa yang kehilangan visi jangka panjang. Kita hanya melihat proyek hari ini, tanpa memikirkan dampaknya 10 atau 20 tahun ke depan. Jalan-jalan yang kita bangun hari ini dengan aspal impor adalah jalan menuju keterikatan ekonomi yang semakin dalam. Dan semakin dalam kita terikat, semakin sulit kita bebas.
Jika kita mau, swasembada aspal bisa dimulai besok. Butuh keberanian untuk memutus mata rantai impor dan memihak pada produksi lokal. Butuh komitmen politik untuk melawan mafia impor aspal yang selama ini diuntungkan. Dan butuh kesadaran rakyat bahwa setiap rupiah yang kita keluarkan untuk impor aspal adalah rupiah yang menjauhkan kita dari kedaulatan.
Kita bisa memilih: terus menjual harga diri demi membeli jalan sendiri, atau berdiri tegak membangun jalan dengan tangan kita sendiri. Pilihan itu bukan hanya soal ekonomi, tetapi juga soal martabat bangsa. Dan martabat tidak pernah bisa diimpor. Martabat hanya bisa dibangun dari keberanian memanfaatkan kekayaan yang Allah titipkan di tanah kita.
Pemerhati Aspal Buton
6 Pengikut

Ketika Allah Menunda, Sebenarnya Dia Melindungi
3 hari laluBaca Juga
Artikel Terpopuler

 0
0




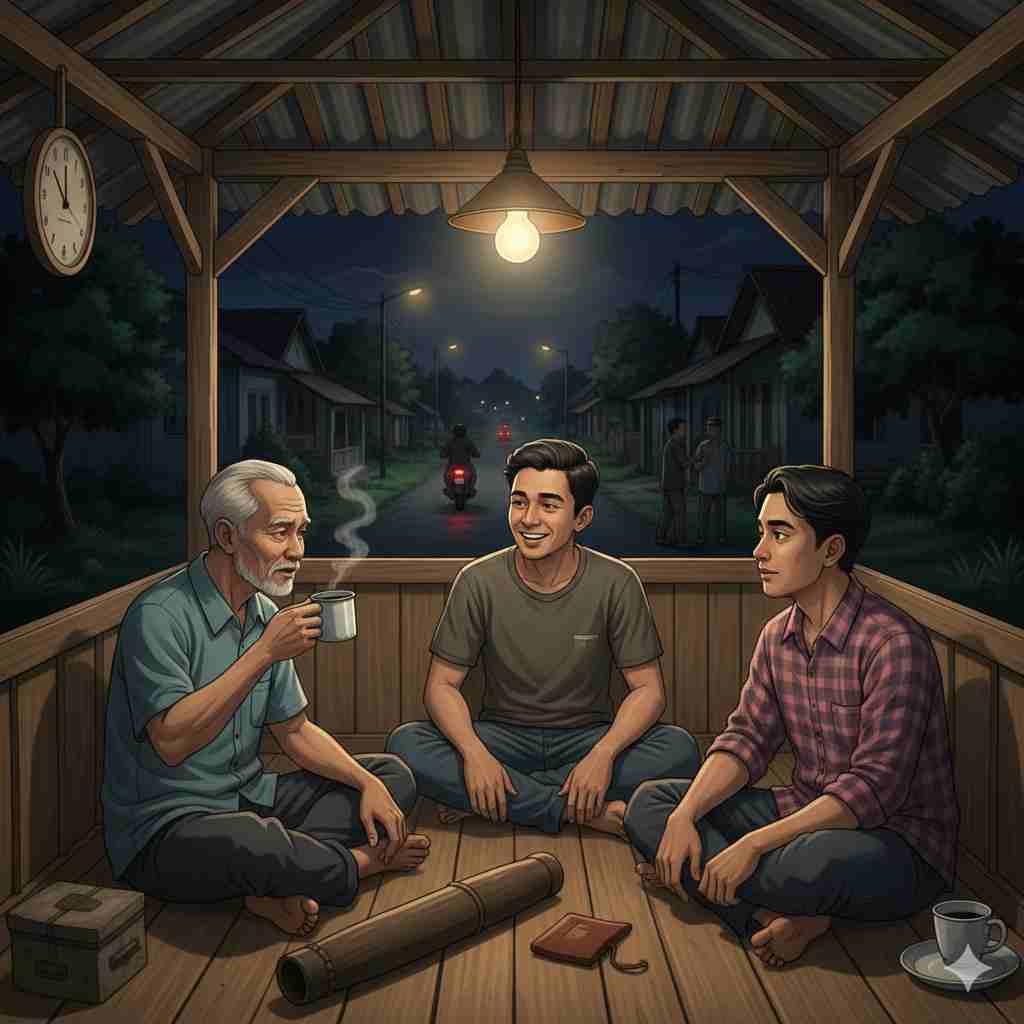

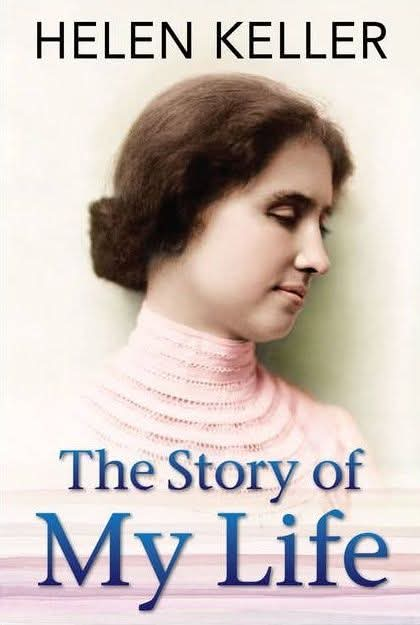
 Berita Pilihan
Berita Pilihan

 99
99 0
0